Masa-masa berdarah di kawan Asia Tenggara tidak hanya terjadi di Indonesia, perbedaan politik antara komunis dan non komunis sering kali menjadi konflik berdarah yang mengerikan. Salah satunya adalah negara tetangga kita Kamboja yang dari segi bahasa sangat berbeda dengan kita, negara tersebut pernah mengalami babak yang sangat mengerikan dengan hantu komunis dibawah rezim komunis Khmer Merah.
Kamboja pernah mengalami perubahan radikal di era kekuasaan rezim komunis-maois. Pada 1975-1979 negara itu dikelola pasukan Khmer Merah yang mendukung Communist Party of Kampuchea atau Partai Komunis Kampuchea (CPK), dan tercatat sebagai salah satu fase paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Khmer Merah dibangun pelan-pelan sepanjang dekade 1960-an di hutan-hutan sebelah timur Kamboja. Mereka didukung tentara Vietnam Utara, Viet Cong (organisasi berhaluan komunis penentang agresi Amerika Serikat dan Vietnam Selatan), dan Pathet Lao (gerakan komunis di Laos).
Amerika Serikat melakukan pengeboman besar-besaran dari pesawat tempur selama Perang Vietnam, termasuk untuk menghancurkan basis kekuatan Khmer Merah. Meski demikian, Khmer Merah tetap mampu memenangkan Perang Sipil Kamboja yang telah berlangsung sejak 17 Januari 1968. Pada 17 April 1975, pasukan Khmer Merah sukses merebut ibu kota Phnom Penh. Time mencatatnya sebagai capaian yang tidak terlalu mengejutkan. Selama perang berlangsung, tentara komunis-maois itu terus-menerus meningkatkan kekuatannya.
Di sisi lain AS telah mundur dari ibu kota, sehingga kejatuhannya tinggal menunggu waktu. Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen, dan Khieu Samphan memimpin rezim baru. Pol Pot menjadi yang paling berkuasa sebab memegang jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Ketua Politbiro dan Komite Sentral CPK. Mereka mengubah nama negara menjadi Kampuchea (per 1976 menjadi Democratic Kampuchea), nama yang lebih disukai golongan komunis ketimbang “Cambodia” (Kamboja). Rekayasa Sosial Penuh Kekejaman Selanjutnya adalah apa yang para sejarawan sebut sebagai “rekayasa sosial” yang radikal. Masyarakat Kampuchea diisolasi dari semua pengaruh asing. Rakyat kota diungsikan semua ke area pedesaan. Bank diberhentikan operasionalnya. Sekolah, rumah sakit, dan sejumlah pabrik juga ditutup.
Sebagaimana rezim menyatakan negara akan memulai “Tahun Nol”, Pol Pot ingin masyarakat Kampuchea “terlahir kembali” melalui kolektivisme dan swasembada absolut. Ia percaya kebijakan itu akan turut merangsang daya produksi kerajinan dan kemampuan industri negara di masa depan. Ada banyak literatur yang membahasnya secara rinci. Salah satunya Sean Bergin dalam The Khmer Rouge and the Cambodian Genocide (2008). Pertama-tama rezim Khmer Merah menjalankan evakuasi penduduk kota Phnom Penh ke wilayah perdesaan. Mereka dipaksa meninggalkan profesi lama untuk terjun membuka lahan persawahan serta mengelola dan memanen padi. Kecuali yang punya kemampuan teknis, mereka dibawa kembali ke kota untuk menjalankan pabrik-pabrik. Di titik ini genosida sebenarnya sudah berlangsung.
Long march yang dilakoni ribuan warga kota ke daerah pinggiran membunuh anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Mereka yang akhirnya sampai di lokasi pun mendapat siksaan serupa karena setiap hari dipaksa kerja dalam waktu yang lama dan dalam kondisi yang mengenaskan. Istirahat dan makan adalah dua hal yang berharga amat mahal. Banyak yang akhirnya meregang nyawa karena tenaganya habis, kelaparan akut, atau diterpa penyakit mematikan seperti malaria. Para pekerja akan dieksekusi jika berusaha kabur dari komune-komune. Pelanggaran aturan, meski yang sepele, juga akan diganjar risiko berat. Pelanggar biasanya akan dipisahkan diam-diam dari pekerja lain, dibawa ke hutan atau persawahan terpencil setelah matahari terbenam, lalu dieksekusi mati.
Entah di tataran elite atau rakyat biasa, pemerintahan Khmer Merah menangkap, menyiksa, maupun mengeksekusi orang-orang yang dianggap sebagai “musuh negara”. Seratus lima puluh penjara dibangun untuk para musuh politik, termasuk dengan mengalihfungsikan gedung-gedung sekolah. Para korban digolongkan mejadi lima kategori menurut Rebbeca Joyce Frey dalam Genocide and International Justice (2009).
Pertama, orang-orang yang punya koneksi dengan pemerintahan sebelumnya, entah itu Republik Khmer, militernya, atau wakil-wakil pemerintahan luar negeri. Kedua, kaum profesional dan intelektual, termasuk mereka yang mengenyam pendidikan tinggi dan mereka yang mengerti bahasa asing. Banyak dari mereka yang berstatus sebagai seniman, musisi, sastrawan, dan pembuat film. Ketiga, etnis Vietnam, etnis Cina, etnis Thailand, dan minoritas lain yang menghuni dataran tinggi sebelah timur. Termasuk juga minoritas Katolik, Muslim, dan biksu-biksu Buddha senior. Katedral Katolik di Phnom Penh dihancurkan. Rezim memaksa umat Islam untuk memakan daging babi. Mereka yang menolak menemui eksekusi mati. Keempat, para “penyabot ekonomi”, yakni mantan penduduk kota yang dianggap bersalah karena tidak mampu menjalankan tugas agrarisnya. Kelima, anggota partai yang dianggap sebagai pengkhianat. Mereka disiksa atau dihilangkan nyawanya—termasuk tokoh senior seperti Hu Nim.
Menghabisi Nyawa Jutaan Manusia Ada banyak versi mengenai total korban jiwa akibat genosida selama kekuasaan Khmer Merah. The Cambodian Genocide Porgram di Yale University, misalnya, memperkirakan korban kematian mencapai 1,7 juta jiwa atau sekitar 21 persen dari total populasi Kamboja pada pertengahan 1970-an. Investigasi PBB menyebut perkiraan yang lebih tinggi: antara 2-3 juta. Sementara itu beberapa peneliti independen menyebut 1,17-3,45 juta jiwa. Jika memakai angka rata-rata, korban kematian Khmer Merah kerap ditampilkan di angka 2 juta. Setengahnya akibat eksekusi. Sisanya karena kelaparan atau penyakit. Rekayasa sosial rezim Khmer Merah dijalankan dengan begitu autokratis, xenofobik, paranoid, dan represif.
Sejarawan memandangnya sebagai jalan bunuh diri. Kenyataannya, Democratic Kampuchea memang hanya bertahan selama empat tahun. Pada April 1978 Pol Pot menyerukan invasi pendahuluan ke Vietnam. Pasukan Khmer Merah menyeberang ke perbatasan, menyerang desa-desa terdekat, membantai warganya, dan menjarah barang-barang berharga. Serangan itu, catat Stephen J. Morris dalam Why Vietnam Invaded Cambodia: Political Culture and the Causes of War (1999), memulai Perang Kamboja-Vietnam. Ada faktor-faktor lain seperti konflik darat dan maritim sepanjang 1975-1978 dan banjir pengungsi perang yang membuat hubungan kedua negara makin keruh.
Vietnam mengerahkan kekuatan militer penuh dalam rangka penyerbuan ke jantung pertahanan Kamboja, termasuk dalam upaya merebut Phnom Penh. Vietnam dibantu oleh Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional (FUNSK), organisasi militan yang terdiri dari eks anggota Khmer Merah yang tidak sepakat dengan bagaimana rezim mengelola Kamboja. Pada 7 Januari 1979 keduanya sukses merebut Phnom Penh, dan otomatis mengakhiri rezim Khmer Merah.
Pemerintahan baru yang diinisiasi aktivis anti-Khmer Merah segera terbangun, dan otomatis tidak diakui oleh sisa-sisa kekuatan Khmer Merah yang melarikan diri ke area dekat perbatasan dengan Thailand. Sisa-sisa kekuatan Khmer Merah bertahan di wilayah tersebut hingga satu dekade setelahnya. Mereka tidak lagi swasembada, tapi berbisnis penyelundupan kayu, berlian, dan makanan. Pendampingnya adalah militer Cina yang bekerja sama dengan militer Thailand. Era 1990-an adalah masa ketika sisa-sisa kekuatan Khmer Merah mulai kelelahan bertarung.
Anggota mereka makin sedikit. Banyak yang menyerahkan diri beserta senjatanya. Donor dari asing makin berkurang. Terjadi perpecahan internal di tataran elite—termasuk dipenjaranya Pol Pot hingga kematiannya pada 1998. Pemimpin lain menyerahkan diri ke otoritas Kamboja untuk kemudian menjalani sidang dengan dakwaan hukuman seumur hidup atau eksekusi mati. Mereka menyatakan permintaan maaf terkait genosida selama berkuasa dulu. Sebelum berganti ke abad-21, Khmer Merah sudah benar-benar habis.
Sumber : tirto.id


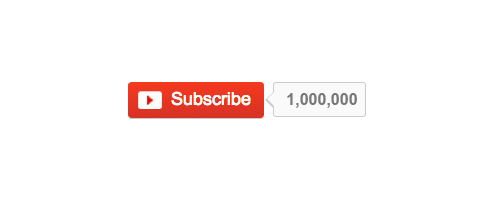









0 komentar:
Posting Komentar